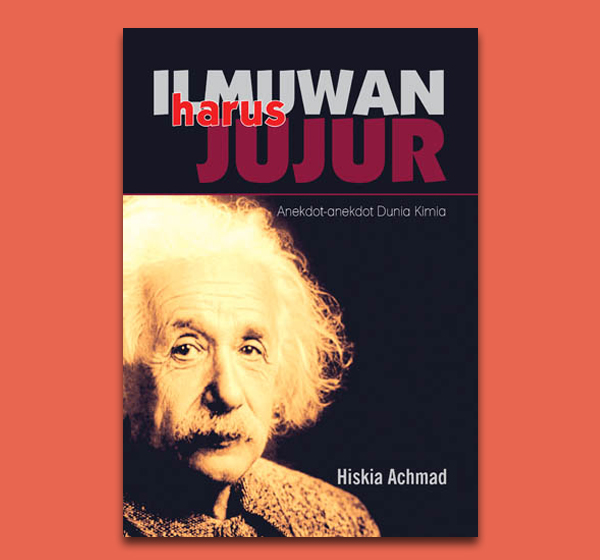Suka-Duka Wawancara*
Bismilllah..
Ini semua tentang mimpi, makin sering kita membayangkannya, membacanya, menuliskannya, berhubungan dengannya entah dengan cara apapun. Semoga akan membuat visualisasi itu semakin nyata. Dan entah kapan, dan dimana, bahkan berkat doa siapa harapan kita akan diwujud.Semoga tetes air setiap waktu sahur akan mempercepat kabulnya doa ku, kamu dan kita.
Penerima Beasiswa Unggulan Dikti 2012
Master in Mechanical Engineering, University of Twente

Halo!
menuntut ilmu di Universiteit Twente. Rasanya tidak perlu saya ceritakan
secara panjang-lebar dari awal sampai akhir bagaimana dramatisnya
perjalanan saya untuk bisa bersekolah di Twente karena –sama seperti
yang lain—tentu saja melibatkan keringat dan kerja keras (empat gagal,
dua tak ada kabar, satu sukses). Alhamdulillah bisa sampai di sini,
dibayarin pula.
berkesan dan membuat saya bersyukur habis-habisan mungkin adalah saat
saya diwawancara oleh pihak pemberi beasiswa, sekitar bulan Mei 2012.
Ketika itu, saya mendapat panggilan wawancara setelah lolos tahap
seleksi dokumen. Dalam surat undangan wawancara, tertulis bahwa acara
yang akan dilakukan adalah “verifikasi dokumen”, yang tentu saja membuat
saya bersiap-siap menyediakan setumpuk dokumen yang mungkin akan
ditanya: hasil tes TOEFL asli, transkrip, ijazah, research proposal,
fotokopi paspor, dan sebagainya. Tak lupa saya menyiapkan daftar
pertanyaan apa saja yang mungkin akan ditanyakan oleh pewawancara,
lengkap beserta jawaban yang telah didiskusikan terlebih dahulu dengan
kakak saya. Walaupun ini merupakan wawancara yang kesekian kalinya dalam
perjalanan saya mencari beasiswa, saya kembali bertanya kepada dosen,
saudara, teman yang sedang kuliah di luar negeri, berlatih monolog dalam
bahasa Inggris, dan tentu saja melakukan simulasi wawancara via skype
dengan kakak saya dan istrinya. Mereka berdua berperan sebagai “the
harshest interviewer ever” dan membantai habis pada setiap jawaban yang
saya berikan. You should try this, people. Nothing’s better than having a totally low self-esteem before your interview!
Pelajaran moral pertama: separah apapun wawancara besok, tak ada yang
bisa mengalahkan research proposal yang dibantai habis oleh kakak
sendiri. Pertanyaan-pertanyaannya yang cepat dan tak disangka-sangka
seperti ini sangat membantu saya berlatih. Tentu saja saran dan evaluasi
dari keduanya juga membuat saya merasa lebih siap keesokan harinya.
Salah satu saran yang menurut saya bagus sekali adalah: lebih baik
bicara lambat dan lancar daripada cepat namun terpatah-patah di tengah
kalimat.
Pada hari-H wawancara, ternyata beberapa pertanyaan yang telah saya
antisipasi benar-benar muncul. Dengan senang hati saya jawab semuanya
dengan penuh percaya diri. Kebetulan pewawancara saya adalah seorang ibu
separuh baya dengan bahasa Inggris yang bagus dan lancar, otak tajam,
dan sering menyela di tengah-tengah kalimat untuk menggali jalan pikiran
saya lebih dalam lagi. Beruntung saya telah dilatih oleh “those two
harshest interviewers ever”, ternyata pertanyaan yang bertubi-tubi
seperti ini cukup membuat saya berkeringat dingin. Contohnya: “Why
do you choose Netherlands?” “Are you sure you can live there?” “Can you
speak Dutch? No??”, “Then how can you be sure that you can finish your
master programme there?”, “And now you choose a specialization that is
not related at all with your previous bachelor project??”, “Let’s see
your research proposal.. From all of these references, is there any
publication written by a Dutch man?”, “Then why do you choose
Netherlands?”, “But why do you choose University of Twente?”, “Oh, I do
know a better university for mechanical engineering, in Germany.”, “This
university is not the best one in Europe. Why don’t you aim higher?”
“Living in Europe is expensive, isn’t it?” (thank God I made a financial
plan last night), etcetera, etcetera, sampai pada akhirnya beliau
meminta saya menunjukkan dokumen-dokumen asli yang diminta. Masalah
muncul ketika beliau bertanya, “Do you have a proof of advisorship?”
Saya bengong, tentu saja. Tak ada kata-kata “proof of advisorship” di
daftar dokumen yang diminta oleh Dikti sebelumnya. Di perguruan tinggi
tujuan saya, tahun pertama diisi dengan kuliah sehingga tesis baru
dimulai pada tahun kedua. Tidak seperti mahasiswa program doktor,
mahasiswa master tidak perlu memiliki dosen pembimbing pada tahun
pertama karena tesis dan spesialisasi yang akan diambil baru ditentukan
pada tahun kedua. Walaupun saya telah mengontak dosen-dosen Twente, saya
belum mempunyai pembimbing tesis resmi, dan itu artinya ada kemungkinan
nama saya akan dicoret dari daftar penerima beasiswa karena dokumen
“proof of advisorship” saya tidak lengkap.
“Uh, no, I do not have it. What do you mean by ‘proof of advisorship’?”Keringat dingin menetes.
Beliau mulai menjelaskan secara singkat-padat-jelas mengenai dokumen
yang dimaksud, yaitu bukti berupa print out email atau korespondensi
apapun yang menunjukkan bahwa ada seorang profesor di Twente yang
bersedia menjadi pembimbing tesis saya. Makin meneteslah keringat dingin
saya.
“I have contacted a professor in Twente by email, is it sufficient? But I do not bring it right now, so may I print it…”
“Sure. Bring it here before 12 o’clock. I’ll be here.”
Kemudian sang pewawancara dengan cueknya menunduk dan menulis sesuatu
di hadapan saya, bahasa tubuh yang cukup jelas mengisyaratkan bahwa sesi
wawancara telah selesai. Dengan mata nanar, saya berjalan ke arah pintu
keluar sambil melihat pelamar-pelamar lain yang masih diwawancara. Meja
sebelah saya sepertinya ceria sekali, pewawancaranya seorang bapak
berambut semburat putih dan pelamar beasiswanya seorang gadis cantik
yang sedang tertawa riang.. (maaf, nggak penting). Anyway, jam
menunjukkan pukul 09.30, jadi saya masih mempunyai waktu sekitar dua
setengah jam untuk mencetak email-email saya dan mendapatkan “proof of advisorship”
itu, entah bagaimanapun caranya. Plan A sampai Z disusun, dengan
kemungkinan terburuk adalah kembali ke tempat wawancara dengan tangan
hampa.
Hal pertama yang saya lakukan yaitu segera kembali ke tempat kos untuk
mendapatkan akses internet, laptop, printer, dan semuanya. Tempat
wawancara cukup jauh dari peradaban, tidak ada printer maupun tempat
nge-print di sekitarnya. Hanya ada masjid. Mungkin kalau saya menyerah,
saya sudah tidur-tiduran dan pasrah berdoa di masjid alih-alih buru-buru
kembali ke rumah kos. Dalam perjalanan pulang ke tempat kos, saya
menelepon kakak kelas saya di Twente dengan harapan mendapat penjelasan
mengenai cara untuk mendapatkan dosen pembimbing dalam waktu kurang dari
dua jam,birokrasi, dan sistem yang berlaku di Twente. Berhubung saya
menelepon jam 10 WIB, di Belanda saat itu masih pukul 5 dini hari dan
kakak kelas saya tak jelas bicara apa. Menelepon Pak Profesor pun tak
mungkin. Akhirnya saya mengirim email kepada beliau dan seorang dosen
lain yang saya harap dapat membantu saya mendapatkan surat “proof of advisorship” tersebut.
Saya sudah pasrah begitu mengetahui bahwa tak mungkin email saya akan
dibalas dalam waktu dua jam. Saya pun kembali ke tempat wawancara dengan
membawa lembaran-lembaran hasil cetakan email percakapan saya dengan
Pak Profesor.
Tepat pukul 12.00 WIB, saya sampai kembali di tempat wawancara dan Ibu
Pewawancara masih menunduk menulis sesuatu di mejanya. Saya serahkan
email korespondensi saya, namun beliau berkata bahwa yang benar-benar
dibutuhkan adalah selembar kertas dengan pernyataan tegas dari seorang
profesor yang bersedia menjadi pembimbing tesis saya. Akhirnya saya
beranikan diri untuk bertanya apakah dokumen tersebut bisa disusulkan
dan alhamdulillah, beliau menyetujui!
Pelajaran moral nomor dua: mungkin saja hal-hal semacam ini terjadi
pada saat wawancara, hanya untuk melihat tingkat keseriusan pelamar
dalam memenuhi tenggat waktu.
Pelajaran moral nomor tiga: siapkan Letter of Advisorship. Walaupun
pihak universitas menolak untuk memberikan surat tersebut karena
mahasiswa S2 masih belum menyelesaikan kuliah tahun pertama, sebaiknya
langsung minta saja ke calon profesor pembimbing.
Singkat cerita, saya mendapatkan
selembar-kertas-berisi-pernyataan-tegas-Pak-Profesor-lengkap-dengan-tanda-tangannya.
Luar biasa, betapa responsif dosen-dosen Twente dalam membantu saya
mendapatkan surat tersebut tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Saya
kumpulkan keesokan harinya, dan alhamdulillah here I am now!